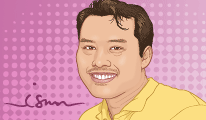Sepertinya ini memang nasib Donna menjadi mitra hidup seorang penulis humor: mengalami kejadian aneh-aneh. Bahkan saat awal kecelakaan pun sudah terlihat.
Saya segera pulang ke rumah saat mendapat kabar jatuhnya Donna. Melihat Donna yang tergeletak pasrah, saya juga tidak berani memindahkannya dengan sembarangan. Langsung saya menelepon bagian UGD suatu rumah sakit.
"Tolong kirimkan ambulans ke rumah saya ya, Mbak," ujar saya pada operator.
"Oh, ada keadaan darurat, Pak?" tanya operator.
Saya sempat tergoda untuk jawab, "Nggak, saya suka aja jalan-jalan keliling kota pake sirene." Namun, berhubung diburu waktu, saya jawab apa adanya, "Istri saya jatuh dari kursi. Mungkin tangannya patah. Dan entah apa lagi. Karena itu saya nggak berani mindahin dia sembarangan."
"Baik, Pak." Ia kemudian menanyakan alamat dan nomor telepon. Beres. Atau saya kira begitu. Karena ia kemudian bertanya, "Bapak nggak perlu perawat, kan?"
"Nggak, istri saya perlunya _dirawat_," ketus saya. "Intinya, saya nggak tahu, Mbak, fungsi perawat itu apa," tambah saya, kalau-kalau operator ini nggak ngerti sarkasme. "Pokoknya tolong kirim ambulans bersama orang yang paham cara memindahkan korban kecelakaan tanpa bikin tambah celaka. Ini darurat!"
"Baik, Pak. Silakan tunggu, ya?"
Lima menit berlalu.
Sepuluh menit.
Lima belas menit.
Telepon kembali berdering. Saya mengangkatnya--ternyata operator tadi. "Halo, Pak. Saya ingin konfirmasi. Ambulansnya jadi nggak?"
"Astaga, Mbaaaak," sahut saya. "Emang sering ya, keadaan darurat yang nggak jadi? Kalau ada yang nelepon karena tabrakan mobil, pernah gitu orangnya nelepon balik terus ngomong, 'Aduh, maaf, ternyata tabrakannya nggak jadi. Ambulansnya gak usah, deh.'"
"Euh, berarti jadi ya, Pak?"
Saya mengerang.
Mungkin dalam bahasa operator erangan berarti "ya" karena ia kemudian berkata, "Baik, Pak. Silakan tunggu, ya?"
Selagi menunggu, datanglah dua teman kantor, Yudi dan Mas Naryo. Berkat itu, saya tidak terlalu senewen. Untung juga kali ini tidak ada konfirmasi lagi. Ambulansnya datang, parkir di depan pagar. Dan keluarlah tim lengkap gawat darurat: satu orang pengemudi. Sudah.
Saya setengah berharap orang ini adalah cyborg medik canggih serbabisa. Namun, komentar pertama orang tersebut langsung membuyarkan harapan saya. Ia melihat sekeliling--hanya ada saya, Yudi, dan Mas Naryo, yang sedang berdiri--dan bertanya, "Yang mana pasiennya?"
"Pak, kalau pasiennya bisa berdiri, saya nggak akan panggil ambulans," ucap saya lirih, sambil menahan lolongan putus asa. Saya lantas memandu sang pengemudi ambulans ke tingkat dua, tempat Donna jatuh. Yudi dan Mas Naryo sigap membantu.
Singkat cerita, Donna berhasil dinaikkan ke atas tandu dan kami bawa turun ke lantai dasar. Saat menuju pintu keluar, Donna mendadak teriak, "A! Jangan lupa!"
"Apaan?" jawab saya panik. Lupa apa nih? Bawa duit? Baju ganti? Nitipin anak?
"Bawa buku!" seru Donna. "Nanti di sana bosen. Ambil Black Rose di dalam kamar. Terus Red Lily di depan komputer!"
"Iya deh," angguk saya, sementara Yudi dan Mas Naryo ngakak.
Donna lantas dinaikkan ke dalam ambulans, ditemani saya. Yudi dan Mas Naryo siap mengikuti dengan kendaraan lain. Sang pengemudi menutup pintu belakang ambulans. Ia naik ke kursi pengemudi dan memasang sabuk pengaman. Lantas ia menoleh ke arah kami dan mengucapkan kata-kata yang tidak akan kami lupakan, "Ke mana?"
Pengemudi sebuah ambulans; dari rumah sakit yang saya telepon; karena mitra hidup saya butuh perawatan; menanyakan kami mau "ke mana?"
Saya bisa membayangkan empat jawaban:
- "Kita coba puter-puter aja dulu sekeliling komplek, Pak. Kalau argonya udah lima puluh ribu, turun, ya?"
- "Terserah Bapak aja, kira-kira tempat makan mana yang enak buat orang yang patah tangan?"
- "Oh, sori. Ini ambulans jurusan Stasiun Hall-Sadang Serang bukan?"
- "Kalau bisa sih ke masa lalu. Tepatnya satu jam sebelum ini. Saya mau menghalangi diri saya menelepon rumah sakit Bapak."